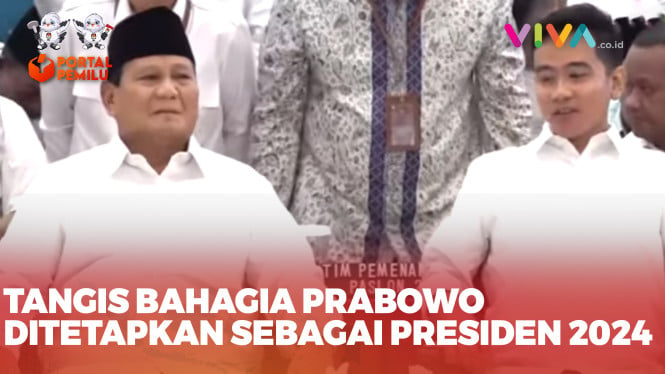Jejak Kekerasan 1965 di Aceh Tengah: Kepala Manusia Diarak di Takengon

- bbc
Salah-satu lokasi penelitian Mustawalad adalah Kampung Mude, Desa Nosar, di pinggir Danau Air Laut Tawar, Takengon.
Pada 1965, sedikitnya 60 orang warga dari desa ini dibunuh karena dituduh komunis.
Siang itu, pada pekan ketiga Oktober 2021, ketika langit berwarna alumunium, saya dan videografer BBC News Indonesia, Anindita Pradana, mengunjungi desa nan tenang itu.
Di salah satu sudut kampung itu berdiri sebuah masjid kuno. Di sanalah, kami bertemu Syahbandar, 52 tahun, salah seorang yang `dituakan`.
Syahbandar mengatakan, tuduhan `desa PKI` itu sangat melukai warga, karena seolah-olah mereka dianggap antiTuhan.
"Itu tidak benar," katanya berulang-ulang. Dia kemudian mengungkapkan beberapa orang warga Desa Nosar yang dibunuh itu adalah "orang-orang pintar".
"Ada isu (mereka yang ditangkap) adalah anti-Tuhan. Itu harus kami bantah, karena mereka yang tertumpas dan kena tangkap adalah tokoh-tokoh (intelektual dan agama)," ujarnya.
Akan halnya ada sekitar 60 orang warga desa itu dibunuh, menurutnya, karena mereka tidak lari. Termasuk seorang imam di kampung itu
"Mereka tidak lari, karena mereka pikir mereka tidak bersalah dan ini adalah negara hukum," kata Syahbandar.
Dia juga menggarisbawahi bahwa kebanyakan warga Nosar yang dibunuh pada 1965 "tidak tinggal di desa, tapi di kota."
Demi membersihkan desa itu dari stigma PKI, Syahbandar bahkan menemui seseorang ulama berinisial TB yang disebutnya ikut terlibat pembantaian atas orang-orang yang dicap komunis di Aceh Tengah.
Baca juga:
- Malam jahanam di hutan jati Jeglong
- Mengungkap kebenaran, menggelar rekonsiliasi
- `Dosa turunan` dicap PKI, keluarga penyintas 65 masih mengalami diskriminasi: `Jangan bedakan kami`
"Dia menyesal, menangis dan bilang `kenapa kita bodoh`, sehingga banyak jatuh korban," ungkapnya.
Di akhir wawancara, Syahbandar mengharapkan peristiwa kekerasan 1965 tidak terulang kembali.
Dia lalu mengutip kata-kata bijak Gayo, yaitu `agih si belem, genap si nge munge`.
"Sudah cukup, jangan terulang lagi," Syahbandar kemudian menerjemahkannya kepada kami.
Untuk menghilangkan residu konflik 1965 di antara warga desa, mereka pun memiliki cara sendiri, yaitu, menggelar upacara adat.
Siapa yang membakar `masjid Bebesan` di Takengon pada Juli 1965?
Ingatan kolektif masyarakat di Aceh Tengah terhadap kekerasan 1965, tidak terlepas pula dari keberadaan sebuah masjid di Takengon.
Masjid Raya Quba di Kecamatan Bebesan dilalap api pada 21 Juli 1965, dua bulan sebelum G30S 1965.
Berbagai laporan menyebut pria yang dituduh membakar masjid adalah anggota atau simpatisan PKI. Namanya Islah.
"Islah adalah anak tiri Tengku Abdul Jalil, ulama berpengaruh di Gayo," tulis Mustawalad di Majalah Pantau, 2008. "Tapi Islah dituduh PKI."
Keterangan polisi saat itu menyebut Islah sebagai pelaku pembakaran, walau masyarakat menyangsikannya, ujarnya.
Islah kemudian dieksekusi oleh tentara di dekat Takengon. Mayatnya kemudian dibiarkan di jalanan dalam kondisi memprihatinkan.
"Ususnya terburai dimakan anjing," ungkap Mustawalad mengutip seorang saksi yang berada di lokasi.
Belakangan ketika pecah G30S 1965, peristiwa kebakaran masjid itu menjadi peletup kemarahan warga di Aceh Tengah terhadap siapapun yang dikaitkan dengan PKI.
Di masa Orde Baru, narasi dominan bahwa pelaku pembakaran masjid adalah anggota PKI bernama Islah, terus dipelihara.
Di Takengon, BBC News Indonesia melihat sendiri ada lukisan tentang kebakaran masjid itu yang disebut pelakunya adalah anggota PKI.
Namun kepada sumber BBC Indonesia, salah satu anak tertuduh, mengatakan ayahnya tidak pernah membakar masjid itu.
Beberapa saksi mata juga disebutnya membantah tuduhan itu. Saat masjid terbakar, Islah sedang bersama istrinya.
"Pria itu bahkan berupaya memadamkannya," ungkap sumber BBC News Indonesia.
Kisah tiga orang warga Takengon dan ikhtiar mereka menyembuhkan `luka 1965`
Lahir dan tumbuh besar di Kota Takengon, Aceh Tengah, tiga orang ini relatif tidak berjarak dengan para keluarga korban 1965 di wilayah itu.
Bahkan ada di antara mereka, anggota keluarganya ditangkap dan dipenjara karena dituduh anggota PKI atau tersangkut G30S 1965.
Dalam cara pandang yang tidak selalu sama, mereka kemudian masing-masing menawarkan `jalan keluar` — sesuai latar profesinya atau keahliannya — bagi para korban.
Selama liputan tiga hari di Takengon, kami menemui Sri Wahyuni (kelahiran 1978), Win Wan Nur (1976) dan Nanda Winar Sagita (1994).
Berikut petikannya:
`Saya menulis cerpen, hutang saya buat paman saya yang dicap PKI` — Sri Wahyuni, pengacara
Salah-seorang pamannya, yang berlatar atase penerjun di TNI AU, pernah dipenjara di Nusa Kambangan karena dianggap terlibat G30S 1965.
Setelah G30S 1965, pamannya memimpin operasi penangkapan Ketua CC PKI Aidit. Namun operasi ini gagal.