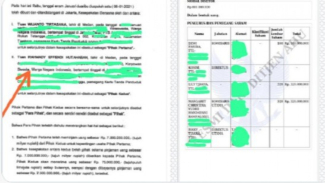Stigma Gangguan Kesehatan Mental: Berakhir Sekarang atau Tidak Sama Sekali
- vstory
VIVA – Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar frasa “gangguan kesehatan mental”. Semoga yang terlintas di pikiran bukan lah kata-kata seperti “berbahaya”, “lemah”, “keterbelakangan mental”, “kurang iman”, atau bahkan “orang gila”. Akan tetapi, sayang seribu sayang, pada realitanya, narasi-narasi tersebut lah yang justru sangat melekat dengan frasa gangguan kesehatan mental.
Ketika frasa “gangguan kesehatan mental” mencuat di kehidupan bermasyarakat, stigma-stigma tertentu kerap kali muncul. Mereka, para penderita gangguan kesehatan mental, kerap dihakimi sebagai orang yang tidak bersyukur atas kehidupannya, orang yang tidak punya pendirian, bahkan sebagai orang yang jauh dari agama ataupun Tuhan. Stigma yang masih sangat melekat dalam kehidupan sosial ini lah yang membuat mereka enggan untuk meminta bantuan dan dukungan dari keluarga, teman, ataupun tenaga profesional. Padahal, semakin cepat seseorang mendapatkan bantuan, akan semakin baik hasil yang didapatkan.
Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2021, secara global, satu dari tujuh anak berusia 10-19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental, menyumbang 13?ri beban penyakit global pada kelompok usia ini. Bahkan, menurut The Lancet Psychiatry, jika beban penyakit global mempertimbangkan cakupan penuh dari konsekuensi kesehatan mental, proporsi tahun hidup dengan kecacatan akibat gangguan kesehatan mental dapat melonjak dari 21% menjadi 32%.
Dari sisi data nasional, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari 6% pada tahun 2013 menjadi 9,8% pada tahun 2018. Data-data tersebut memperlihatkan betapa gentingnya permasalahan kesehatan mental baik secara nasional maupun global.
Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi gangguan kesehatan mental adalah stigma yang masih mengakar di kehidupan sosial. Stigma kesehatan mental mengacu pada ketidaksetujuan masyarakat atau ketika masyarakat mendiskreditkan dan mendiskriminasi orang yang hidup dengan gangguan kesehatan mental ataupun orang yang mencari bantuan karena tekanan emosional, seperti kecemasan, depresi, gangguan bipolar, atau PTSD.
Stigma kesehatan mental dapat berasal dari stereotip, yang merupakan keyakinan atau representasi yang disederhanakan atau digeneralisasi dari seluruh kelompok orang, yang seringkali tidak akurat, negatif, dan menyinggung. World Health Organization (WHO) pada tahun 2001 menyatakan bahwa stigma adalah salah satu hambatan terbesar bagi para penderita dalam keterlibatan pengobatan terhadap gangguan kesehatan mental, meskipun pengobatan telah terbukti efektif, bahkan di negara berpenghasilan rendah.
Stigma kesehatan mental bukan hanya masalah interpersonal, melainkan adalah sebuah krisis kesehatan. Semakin mengakar stigma kesehatan mental, akan semakin sulit juga upaya penekanan prevalensi gangguan kesehatan mental. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sekaligus menghilangkan stigma kesehatan mental?
Pertama, kita bisa mengatasinya dengan berbicara secara terbuka terkait kesehatan mental. Kita perlu menjadikan isu kesehatan mental sebagai isu yang tidak tabu di kalangan masyarakat. Selama kesehatan mental masih menjadi perkara yang tabu, pembicaraan terkait kesehatan mental akan selalu terlihat sebagai sesuatu yang tidak penting sehingga pada akhirnya para penyintas gangguan kesehatan mental akan semakin kesulitan untuk mendapatkan pertolongan.
Dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan “apa kabar?” seharusnya tidak menjadi kata-kata yang digunakan untuk sapaan semata, tetapi pertanyaan tersebut harus menjadi sebuah pertanyaan penuh makna yang benar-benar menanyakan kabar setiap individu secara fisik ataupun mental. Kurangnya percakapan tentang kesehatan mental telah menghalangi banyak orang untuk menerima cinta dan perhatian yang mereka butuhkan untuk mengatasi gangguan yang mereka alami.
Selain itu, kita bisa berkontribusi dengan cara mengedukasi diri sendiri dan orang lain terkait kesehatan mental. Bentuk edukasi yang kita berikan akan sangat membantu dalam merespons kesalahpahaman masyarakat terkait kesehatan mental. Edukasi yang disebarluaskan pun bisa menjadi upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesehatan mental agar masyarakat bisa lebih memahami seperti apa kehidupan bagi mereka yang hidup dengan kondisi gangguan kesehatan mental sehingga pada akhirnya stigma-stigma bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.
Penyebarluasan edukasi ini tidak hanya akan mendidik masyarakat dan membantu mengurangi stigma, tetapi juga dapat memberikan keberanian kepada mereka yang menghadapi tantangan serupa dan membantu mereka untuk mendapatkan bantuan.
Upaya lain yang bisa kita lakukan adalah dengan mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka yang menderita gangguan kesehatan mental. Hal-hal kecil yang kita katakan atau lakukan dapat membuat perbedaan besar bagi mereka. Cukup dengan memberikan mereka ruang untuk berbicara dan mendengarkan perasaan mereka bisa sangat membantu.
Dampingi mereka tanpa prasangka apa pun dan perhatikan setiap kalimat yang akan kita sampaikan kepada mereka. Jika mereka merasa kesulitan, beritahu mereka bahwa kita akan selalu ada pada saat mereka siap untuk berbicara mengenai kesulitan yang mereka alami.
Mereka, yang berjuang atas gangguan kesehatan mentalnya, berhak atas kehidupan dan kesempatan yang sama seperti orang lain. Bukan lah tangan-tangan yang menunjuk dengan penuh prasangka dan bukan pula tatapan sinis penuh penghakiman yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka membutuhkan uluran tangan dan tatapan hangat dari kita semua yang menyiratkan pesan bahwa “kalian tidaklah sendirian”. (Yaneva Azzahra, Departemen Sosial Masyarakat BEM IM FKM UI)